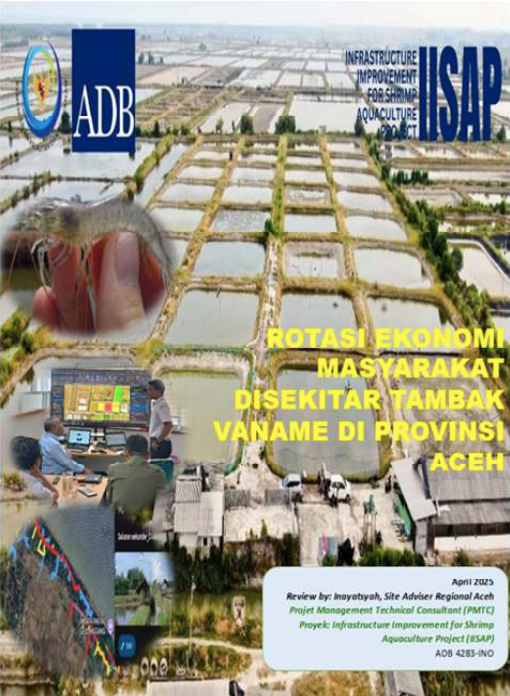
Rotasi Ekonomi Masyarakat di Sekitar Tambak Udang Vaname di Provinsi Aceh
Rotasi Ekonomi Masyarakat di Sekitar Tambak Udang Vaname di Provinsi Aceh
Oleh : Inayatsyah
Site Advisor Program IISAP Aceh
Luas lahan/Topografi
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi perikanan yang sangat besar, baik untuk mendukung ekspor maupun memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, subsektor perikanan menyumbang 2,58% terhadap sektor pertanian nasional, menempatkannya di posisi kedua setelah perkebunan (3,76%), dan di atas kehutanan (0,60%), peternakan (1,52%), serta hortikultura (1,44%). Hal ini menunjukkan adanya peluang pengembangan produksi perikanan Indonesia sebagaimana diidentifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Potensi ini semakin diperkuat oleh wilayah-wilayah strategis seperti Provinsi Aceh, yang memiliki garis pantai sepanjang 1.660 km dan luas perairan laut mencapai 295.370 km², terdiri dari perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Sumber daya ikan laut di Aceh diperkirakan mencapai 272,7 ribu ton per tahun, dan menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh tahun 2023, potensi produksi perikanan daerah ini mencakup 297.222 ton dari perikanan tangkap, 103.815 ton dari budidaya pembesaran, serta 1,66 miliar ekor dari budidaya pembenihan. Angka-angka tersebut mencerminkan kontribusi signifikan dari berbagai kabupaten dan kota di seluruh Aceh dalam mendorong pertumbuhan sektor perikanan nasional.
Luas lahan dan topografi Aceh sangat mendukung pengembangan program Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP) yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), khususnya melalui pendekatan klaster tambak udang yang melibatkan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan). Pendekatan ini terbukti efektif karena memudahkan pelatihan, distribusi bantuan, dan peningkatan hasil panen. Di Aceh Timur, misalnya, klaster IISAP berhasil meningkatkan produksi dan memperkuat ekonomi masyarakat tambak. Dalam pelaksanaannya, IISAP mendorong pendekatan klaster yaitu pengelolaan tambak secara bersama oleh kelompok pembudidaya yang tergabung dalam Pokdakan. Pokdakan inilah yang menjadi wadah formal petambak dalam menerima berbagai bentuk dukungan, seperti bantuan sarana dan prasarana, pelatihan teknis, pendampingan, hingga akses ke pasar dan pembiayaan.
Untuk wilayah Aceh Utara, jumlah anggota kelompok yang terdata saat ini adalah sebanyak 329 orang yang tergabung dalam 19 kelompok. Di Kabupaten Bireuen, terdapat 20 kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) tradisional maupun tradisional plus, dengan total anggota mencapai 370 orang. Selain itu, ada tambahan satu pokdakan klaster yang beranggotakan 10 orang. Sementara itu, di Kabupaten Pidie Jaya, tercatat 659 orang anggota dari kelompok tradisional, ditambah 12 orang dari kelompok klaster. Dengan demikian, total anggota penerima program ISAP di kabupaten ini berjumlah 671 orang, yang tersebar di 23 kelompok tradisional dan satu kelompok klaster. Untuk Kabupaten Aceh Besar, jumlah anggota dari tambak tradisional sebanyak 143 orang yang tersebar dalam 11 kelompok, ditambah satu pokdakan klaster dengan 11 anggota. Adapun di Kabupaten Pidie, tercatat sebanyak 210 orang anggota, Secara umum, jumlah kelompok dan anggota di masing-masing kabupaten menunjukkan variasi yang cukup signifikan, tergantung pada kondisi wilayah dan pendekatan budidaya yang digunakan, baik tradisional maupun klaster.
Kondisi pra Tsunami/Pasca Tsunami
Sebelum bencana tsunami tahun 2004, sektor perikanan di Aceh menjadi salah satu sektor ekonomi utama, khususnya bagi masyarakat pesisir. Aktivitas perikanan tangkap dan budidaya tambak air payau terutama udang windu dan bandeng telah berkembang luas di berbagai wilayah seperti Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Timur. Sistem usaha pada masa itu masih didominasi oleh nelayan kecil dan petambak tradisional, namun tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan rumah tangga dan perekonomian lokal (Syamsidik et al., 2015; Fahmi et al., 2017). Meski menjanjikan, sektor perikanan pra-tsunami menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan teknologi, akses pasar yang terbatas, serta infrastruktur pendukung yang belum merata. Hal ini menyebabkan sektor ini sangat rentan terhadap gangguan besar seperti bencana alam. Tsunami 2004 menjadi bukti nyata, di mana infrastruktur hancur, lahan tambak rusak akibat intrusi air laut, dan alat tangkap hilang, mengakibatkan pemulihan yang sangat lambat dan perubahan besar dalam mata pencaharian masyarakat.
Dalam buku "Aceh Pasca Lima Belas Tahun Tsunami" dijelaskan bahwa Tsunami 2004 yang menghantam Aceh memberikan dampak terparah di Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, dan Aceh Jaya, sementara wilayah pantai timur seperti Pidie, Bireuen, dan Lhokseumawe mengalami kerusakan relatif lebih kecil. Berdasarkan evaluasi Februari 2005, infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan transportasi mengalami kerusakan signifikan yang dimana 1.488 sekolah rusak yang menyebabkan terganggunya pendidikan 150.000 siswa, 26 Puskesmas hancur, serta 9 pelabuhan dan 230 km jalan rusak berat. Lingkungan dan lahan pertanian juga terdampak parah dengan 11.000 hektar perkebunan mengalami kerusakan (2.900 hektar rusak permanen) dan kerusakan terumbu karang mencapai 90%. Akibatnya, perekonomian Aceh diperkirakan melemah hingga 15% pada tahun 2005 .
Sebuah studi yang dilakukan oleh Fahmi et al. (2017) di Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, menggambarkan proses pemulihan yang berlangsung sangat lambat. Dari total 149 hektar tambak yang ada sebelum tsunami tahun 2003, hanya sekitar 28 hektar atau 19% yang berhasil dipulihkan dan digunakan kembali hingga tahun 2015. Penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor lingkungan seperti perubahan kualitas tanah dan salinitas, tetapi juga karena banyak petambak yang memilih beralih profesi akibat ketidakpastian dan lamanya proses pemulihan. Penelitian lain oleh Syamsidik, Iskandar, dan Rasyif (2015) juga menegaskan bahwa dampak bencana terhadap masyarakat pesisir tidak bersifat sementara. Proses pemulihan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat di wilayah pesisir ternyata memakan waktu lebih dari satu dekade dan bahkan hingga kini belum sepenuhnya kembali seperti semula. Hal ini menunjukkan bahwa bencana alam bukan hanya soal kerugian fisik, tetapi juga menyisakan dampak sosial dan ekonomi yang panjang, yang menuntut pendekatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih menyeluruh, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan lokal.
Besaran Produksi Ekspor
Komoditas udang memegang peranan penting dalam sektor perikanan Indonesia, terbukti dari kontribusinya yang signifikan terhadap ekspor produk perikanan nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dikutip dalam Booklet Profil Pasar Udang KKP 2023, udang menyumbang sebesar 34,5 persen dari total ekspor produk perikanan Indonesia.Puncak nilai ekspor udang tercatat pada tahun 2021, yakni sebesar USD 2,23 miliar. Namun demikian, pada tahun 2022 nilai tersebut mengalami sedikit penurunan sebesar 3,22 persen menjadi USD 2,16 miliar. Meskipun demikian, tren jangka panjang menunjukkan pertumbuhan positif, dengan rata-rata pertumbuhan ekspor udang Indonesia sebesar 4,61 persen per tahun selama periode 2017–2022. Dari sisi produksi, Indonesia mencatatkan peningkatan yang cukup signifikan. Produksi udang nasional pada tahun 2022 mencapai 1.099.976 ton, naik 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 953.177 ton. Tiga jenis udang yang menjadi komoditas utama adalah udang vaname (Lithopenaeus vannamei), udang windu (Penaeus monodon), dan udang jerbung (Penaeus merguiensis), dengan udang vaname sebagai jenis yang paling dominan. Udang ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2001, dan kini menyumbang lebih dari 75 persen dari total produksi udang nasional.
Dalam hal bentuk produk yang diekspor, data tahun 2022 menunjukkan bahwa udang mentah beku mendominasi dengan porsi sebesar 67,9 persen, disusul oleh udang matang dan breaded beku sebesar 23,1 persen, serta kategori lainnya sebanyak 9,0 persen. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa udang merupakan komoditas strategis dalam mendukung ketahanan ekonomi sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Meskipun terdapat fluktuasi tahunan, tren pertumbuhan ekspor dan produksi menunjukkan prospek yang menjanjikan ke depan, khususnya dengan optimalisasi budidaya udang vaname yang terus meningkat.
Pendapatan daerah dari sektor tambak vaname di Aceh
Program budidaya udang vaname di Aceh, yang didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui program Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP), telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produktivitas dan perekonomian daerah. Beberapa wilayah seperti Aceh Besar dan Aceh Tamiang mencatat peningkatan pendapatan signifikan dari siklus panen udang intensif, bahkan mencapai ratusan juta rupiah per siklus.
Meskipun data spesifik mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tambak udang vaname di Aceh belum tersedia secara langsung, beberapa indikator menunjukkan kontribusi signifikan sektor ini terhadap perekonomian daerah. Sebagai contoh, di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, pendapatan dari budidaya udang vaname intensif mencapai Rp206.731.170 pada siklus pertama, Rp127.031.460 pada siklus kedua, dan Rp156.338.834 pada siklus ketiga. Selain itu, di Kabupaten Aceh Tamiang, KKP memberikan dukungan berupa satu paket klaster tambak udang vaname berkelanjutan senilai Rp5.868.658.000. Investasi ini tidak hanya meningkatkan produksi udang, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Di Aceh Timur, misalnya, produksi mencapai 25 ton per musim panen dengan nilai sekitar Rp1,8 miliar. Di Aceh Tamiang, produktivitas tambak tradisional yang sebelumnya hanya menghasilkan sekitar 250 kg per hektare meningkat menjadi 12–15 ton per hektare per siklus panen. Keberhasilan ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petambak dan membuka peluang usaha baru di sektor-sektor pendukung. Selain dukungan dari pemerintah pusat, sejumlah kabupaten di Aceh juga mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta Dana Desa untuk mengembangkan sektor ini. Contohnya, kelompok budidaya udang vaname di Aceh Barat Daya menerima bantuan senilai Rp500 juta, sementara Desa Kabong di Aceh Jaya memanfaatkan Dana Desa dalam jumlah yang sama untuk mengembangkan tambak vaname yang dikelola oleh BUMG. Usaha ini menjadi salah satu sektor unggulan desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
Kendala
Sektor kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah Aceh, tengah menghadapi tantangan kompleks yang saling berkaitan dengan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya laut membuat sektor ini sangat rentan terhadap perubahan lingkungan dan praktik pengelolaan yang kurang berkelanjutan. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya mengancam kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem laut, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat nelayan, ketersediaan pangan lokal, serta stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Solusi
Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan yang terpadu, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat pesisir menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sektor ini. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, Aceh dapat mengoptimalkan potensi kelautannya secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah di masa mendatang sehingga mewujudkan Astacita program pemerintahan secara nasional (Inayatsyah-SA Aceh)



